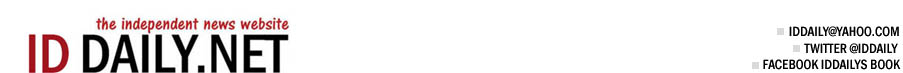Balgis Muhyidin
Andai boleh kupinta hari
‘tuk selalu
Seputih hari nan fitrie
Agar ada maaf
Untuk semua kealphaan
Dari kodrat insani
Kuucap namaMU
Di hembusan surgawi Ramadhan
Seindah kalam yang telah KAU janjikan
KarenaMU
Kumencoba melintasi hari
Mencoba mengendalikan diri
DipintuMU
Aku mengetuk
Meski aku terseok dengan beban pertanyaan yang sulit terjawab
Pintaku
Putihkan hatiku ‘bak salju
Setelah perjalanan yang melelahkan
Agar bisa kuberikan senyum
Meski luka tertorehkan
KarenaMU
Kutahu, kumampu
KarenaMU
Genderang bedug takbir mengalun merdu
Tulisan diatas saya buat sekitar 13-14 tahun yang lalu. Saya bagikan pada teman-teman Indonesia saya yang kebanyakan waktu itu berada di Paiton Project. Teman sekretaris yang tidak sekantor dengan saya bercerita, bahwa salah satu Engineer di perusahaannya sampai bertengkar dengan istrinya gara-gara tulisan tersebut. Istrinya bertanya, kenapa tulisannya sangat personal banget, dia punya hubungan apa dengan si penulis/ pengirim hingga tulisan itu harus nyampe ke rumah mereka.
Saat itu saya cuek saja, karena tulisan itu juga saya berikan kepada sekitar lima puluh teman lainnya, yang merayakan Idul Fitri. Sahabat dan teman bagi saya sangatlah special, canda dan tawa kami bagi bersama. Namun, mereka semua sama tiada beda. Saya menyayangi mereka, itu aja. Menurut saya, tulisan itu adalah bentuk kecintaan saya padaNYA, bukan pada seseorang. Itu alasan saya waktu itu, pendeknya ‘emangnya gue pikirin?’.
Namun saat ini saya memikirkannya. Siapapun wanita itu (istri engineer itu) jika dia membaca tulisan ini, dari relung hati yang terdalam saya memohon maaf. Niat saya waktu itu (menurut saya) didasari niat baik, membagi cinta saya padaNYA kepada sahabat-sahabat saya. Mendapatkan cintaNYA, dengan meniti tangga maaf dari orang-orang disekeliling saya. Namun apa gunanya niat baik tersebut, jika ternyata melukai hati orang lain?
Belajar dari pengalaman tersebut, saya sadari banyak hal dalam kehidupan menghadapkan saya pada situasi dilematis. Kejadian maupun keputusan yang menurut saya ‘baik-baik’ saja belum tentu baik bagi orang lain. Dalam keseharian saya, disengaja atau tidak banyak sekali catatan-catatan tersebut mengiringi semua interaksi saya. Interaksi saya kepada sesama. Ketika saya menyandang kodrat saya, sebagai manusia. Untunglah saya diberi kesempatan untuk meminta maaf, meskipun saya setuju permintaan maaf itu tidak harus menunggu lebaran. Salah satu keindahan ritual tahunan ini adalah mengingatkan kita untuk selalu bermaaf-maaf-an. Yang kadang sering terlupakan.
Saya pernah mendapatkan sebuah kartu post yang cantik dengan tulisan: Maafin saya ya?? Score kita sekarang 0-0. Ketika itu saya menganggapnya biasa-biasa saja, emangnya sepak bola? Score 0:0? Teman saya benar, coba bayangkan jika catatan-catatan yang berisi kealphaan scorenya bukan 0:0, tapi menjadi 124765 : 190872 (kali 100 kalau kita punya teman 100 – meskipun masing-masing angkanya bisa berbeda) atau kali 1000 jika teman kita 1000 orang. Bagaimana kita bisa meraih fitri, dan hati kita kembali putih? Kembali bersih? Serasa bayi yang baru dilahirkan? Ketika catatan-catatan tersebut masih belum termaafkan? Ketika semua teman kita belum mengosongkan kekhilafan, belum menghapus semua kealphaan? Belum memberikan score nol untuk kita, dan kitapun belum memberikan score nol untuknya?
Menurut pemahaman saya, dengan memberikan score nol untuk semua kekhilafan adalah salah satu bentuk kebesaran hati. Dengan memberikan score nol, kita telah mengalahkan hasrat manusiawi kita untuk selalu mengingat kesalahan orang lain. Meluluh lantakkan ke egoan kita dan menggantinya dengan cinta, dengan kasih. Menurut saya, Islam adalah kelembutan, adalah kasih. Bagaimana bisa, kita membiarkan spons spons hati kita berdarah-darah dengan kebencian dan kedengkian dengan selalu mengingat kekhilafan dan kealphaan orang lain? Dengan score nol kita berusaha mendekati kesempurnaan fitrah kita sebagai manusia, memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri.
Dalam kesempatan ini ijinkanlah saya dari segala kedunguan saya sebagai manusia yang kadang terlalu sok pintar, terlalu merasa bahwa apa yang saya lakukan selalu benar. Sehingga mengabaikan ruang-ruang lain yang sebenarnya berisi kebenaran hakiki. Terlalu sok tahu tentang kedalaman hati manusia, padahal hanya secuil pengetahuan saya tentangnya. Bagaimana saya bisa, memastikan hal yang baik untuk orang lain, manakala saya sendiri melakukan kesalahan terhadap keputusan yang saya ambil?
Bahkan kadang saya sering tidak tahu apa yang saya inginkan? Bagaimana bisa, saya memastikan seolah saya paham keinginan orang lain? Untuk itu teman, perkenankan saya meminta maaf. Agar teman-teman bisa mengosongkan lembaran-lembaran khilaf dan alpha. Agar score kita menjadi 0:0. Tapi untuk catatan yang baik, jangan 0:0 dunk….semoga semakin banyak dan banyak sehingga menjadi salah satu bekal baik kita kelak ketika mesti menghadapNYA.
Seandainya boleh kupinta hari-hari ……selalu seperti hari nan fitri….putih…bersih…
Minggu, 20 September 2009
Jumat, 04 September 2009
Menjadi Ibu
Balgis Muhyidin
Pergulatan ini mungkin berbeda antara wanita yang satu dengan yang lain. Pilihan-pilihan yang diambilpun akan berbeda. That’s fine. Yang saya tulis ini adalah pergulatan saya. Pilihan saya. Bisa dikatakan hampir separo hidup saya, saya sudah bekerja. Saya mulai bekerja sejak usia saya 21 tahun, semasa menempuh S1. Delapan belas tahun tepatnya. Uang dari bekerja saya gunakan untuk membiayai kuliah. Meskipun saat itu, sebagian kebutuhan masih ditopang orang tua.
Ketika saya menikah dan hamil, pesan Ayah saya almarhum: jangan pernah berhenti bekerja, tanpa pekerjaan laki-laki akan semena-mena terhadapmu. Maksud ayah, saya harus punya karir diluar rumah yang cemerlang. Meskipun saya tahu, ibu saya hanyalah ibu rumah tangga biasa. Toh, ayah sangat mencintainya. Hingga akhir hayat beliau ayah selalu memanggil ibu dengan sebutan ‘Jeng. Kependekan dari ‘diajeng’. Meskipun mereka berdua bukan orang jawa.
Di rumah, terkesan ayah selalu menurut nasehat yang ibu berikan. Saya mencintai ayah, apapun yang beliau sampaikan selama ini saya rasakan kebenarannya. Saat itupun, saya bertekad untuk menjadi seperti harapan beliau. Mempunyai keluarga, menjadi ibu dan punya uang dari hasil keringat sendiri. Sungguh tidak terbayangkan bagaimana rasanya jika saya hanya menunggu uang ‘jatah’ dari suami. Meskipun dalam Islam kecukupan financial adalah tanggung jawab laki-laki.
Putra pertama kami lahir. Kami mempunyai pembantu yang luar biasa menyayanginya. Meskipun kadang ketika berangkat bekerja putra kami menangisi kepergian saya. Saat itu hati saya mulai teriris. Ketika putra kami masuk rumah sakit karena sesuatu hal, saya menemaninya dua hari. Setelah itu kantor mengharuskan saya keluar kota. Masih saya ingat salah satu pembezuk yang masih kerabat kami mengatakan saya cukup ‘kuat’ meninggalkannya. Saat itu kondisi putra kami mulai membaik dan saya pikir dia berada ditangan yang tepat. Dokter. Dan kebetulan suami saya tidak sedang keluar kota. Apa yang salah?
Putra kedua kami lahir. Kami tidak menemukan pembantu sebaik seperti sebelumnya. Sampai dengan sekarang putra kedua kami belum lancar berkata-kata. Mungkin ketika kami bekerja tidak ada yang mengajaknya bercakap-cakap. Buktinya ketika saya cuti melahirkan anak ketiga selama tiga bulan. Kosa katanya meningkat. Di dalam relung hati yang terdalam saya menyalahkan diri saya sendiri. Jika saya selalu disampingnya, mungkin dia akan secerewet kakaknya.
Setiap kali akan berangkat ke kantor kami harus berputar-putar mengelilingi perumahan kami, bersama putra kedua kami. Jika tidak dia akan menangis histeris, sehingga kami miris. Seandainya saya bisa selalu membawanya. Mendekapnya selalu.
Ketika putri ketiga kami lahir. Proyek tempat saya terakhir bekerja usai April tahun ini. Usia putri kami enam bulan. Biasanya sebelum proyek yang satu selesai, saya sudah mendapatkan proyek lainnya. Namun tidak kali ini.
Saya merasa kehilangan waktu-waktu bersama mereka. Waktu-waktu yang tidak akan pernah kembali. Waktu mereka merangkak pertama kali, waktu mereka bicara pertama kali dan waktu waktu lain yang tidak akan pernah tergantikan. Saya takut saya akan menyesalinya kelak. Saya lebih takut lagi karena saya tidak tahu banyak kebiasaan mereka. Bagaimana kami akan berbincang, manakala saya tidak tahu topik-topik yang mereka sukai?
Seringkali saat saya berada diluar kota, saya mendapat kabar bahwa anak kami sakit. Duh, inginnya saya bisa terbang saat itu juga dan memastikan mereka tidak apa-apa. Atau saya berada di suatu tempat yang sangat indah, menyenangkan. Rasanya saya tidak bisa menikmatinya manakala saya hanya sendirian. Yang saya bayangkan adalah, alangkah bahagianya jika putra-putri kami juga bisa menikmatinya.
Saya punya teman-teman beragam. Ada yang sampai sekarang belum menikah dan menjadi wanita karir yang hebat. Ada yang sudah menikah, punya anak dan tetap menjadi wanita karir yang hebat. Ada juga teman saya yang sejak awal menikah memutuskan untuk berada dirumah saja. Sekarang saya jadi tahu, menjadi ibu adalah peran yang sungguh luar biasa. Sebagaimana salah satu iklan di televisi.
Ibu, disadari atau tidak adalah tenaga keuangan yang hebat, mencukupkan berapapun uang yang diberikan uantuk memenuhi kebutuhan rumah dan jika mungkin untuk ditabung. Ibu, adalah tenaga pengajar yang harus serba tahu karena menjadi rujukan setiap pertanyaan. Ibu, adalah perawat atau dokter yang ahli sehingga kasus pilek, panas karena sakit gigi bisa ditangani segera sebelum dibawa ke praktek dokter. Jika anaknya alergi, Ibu juga harus memastikan makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang tidak akan memicu alergi anaknya. Dan tugas-tugas lain yang dikerjakannya dengan penuh cinta.
Maka tidak salah jika pepatah mengatakan, dari ibu yang hebat akan muncul anak-anak yang hebat. Di dalam Islam dikatakan surga terletak dibawah kaki ibu.
Saya tahu itu, namun sungguh tidak mudah Kesibukan-kesibukan itu bukan kesibukan yang biasa saya jalani. Pekerjaan-pekerjaan ini bukan pekerjaan yang biasa saya lakukan. Namun memandang putra-putri kami, tangan mereka yang kadang memeluk leher saya dan minta cium setiap saat, adalah kekuatan tersendiri. Kata-kata ayah saya masih sering terngiang, namun saya tidak ingin mendebatnya. Saya hanya ingin berada disamping anak-anak kami. Memeluk dan mengelus mereka kapanpun saya mau. Mendengarkan cerita-cerita mereka setiap hari. Hanya itu.
Ketika keputusan itu, saya sampaikan pada salah satu teman, pertanyaannya adalah: Bisakah? Rasanya secara nalar memang tidak bisa, namun kenyataannya selama empat bulan ini dengan segala cerita didalamnya, saya bisa. Saya menikmatinya. Memastikan kepada putra-putri kami saya ada kapanpun mereka butuhkan. Mencintai mereka tanpa ada syarat. Tanpa ada habisnya. Meskipun, tidak mempunyai uang sendiri sungguh tidak nyaman.
Salah satu teman ada yang mengatakan, jika suatu saat kamu ingin bekerja lagi pasti akan sulit. Biasanya jika kita berhenti, jeda beberapa saat akan sulit mendapatkan pekerjaan lainnya. Entahlah, saya hanya ingin mengikuti naluri saya. Naluri saya sebagai seorang wanita, sebagai ibu. Mungkin memang ada yang mesti dikorbankan. Yang saya tahu, saya tidak akan menjadi wanita sempurna, hanya dengan melahirkan saja. Menurut saya, saya akan menjadi wanita yang sempurna jika anak-anak kami menjadi orang yang berguna bagi sesama, mampu berempati terhadap orang lain, mempunyai ahlak yang baik.
Saat inilah nilai-nilai itu mesti kami tanamkan bersama. Mungkin ada yang bisa, dengan tidak mendampingi mereka setiap saat. Dengan menekankan pada kualitas waktu. Masing-masing orang punya cara berbeda mengungkapkannya. Cara saya, mengikuti naluri saya, merengkuh mereka dalam pelukan. Membantu mereka menjadi diri sendiri. Mendampingi mereka meraih mimpi. Saat ini saya mesti menggandeng tangan-tangan mungil mereka, menunjukkan arah dan jalannya. Pekerjaan ini menurut saya, tidak bisa saya delegasikan kepada orang lain. Sehebat apapun mereka. Karena hanya saya ibu mereka.
Taman Indah, September 2, 2009.
Pergulatan ini mungkin berbeda antara wanita yang satu dengan yang lain. Pilihan-pilihan yang diambilpun akan berbeda. That’s fine. Yang saya tulis ini adalah pergulatan saya. Pilihan saya. Bisa dikatakan hampir separo hidup saya, saya sudah bekerja. Saya mulai bekerja sejak usia saya 21 tahun, semasa menempuh S1. Delapan belas tahun tepatnya. Uang dari bekerja saya gunakan untuk membiayai kuliah. Meskipun saat itu, sebagian kebutuhan masih ditopang orang tua.
Ketika saya menikah dan hamil, pesan Ayah saya almarhum: jangan pernah berhenti bekerja, tanpa pekerjaan laki-laki akan semena-mena terhadapmu. Maksud ayah, saya harus punya karir diluar rumah yang cemerlang. Meskipun saya tahu, ibu saya hanyalah ibu rumah tangga biasa. Toh, ayah sangat mencintainya. Hingga akhir hayat beliau ayah selalu memanggil ibu dengan sebutan ‘Jeng. Kependekan dari ‘diajeng’. Meskipun mereka berdua bukan orang jawa.
Di rumah, terkesan ayah selalu menurut nasehat yang ibu berikan. Saya mencintai ayah, apapun yang beliau sampaikan selama ini saya rasakan kebenarannya. Saat itupun, saya bertekad untuk menjadi seperti harapan beliau. Mempunyai keluarga, menjadi ibu dan punya uang dari hasil keringat sendiri. Sungguh tidak terbayangkan bagaimana rasanya jika saya hanya menunggu uang ‘jatah’ dari suami. Meskipun dalam Islam kecukupan financial adalah tanggung jawab laki-laki.
Putra pertama kami lahir. Kami mempunyai pembantu yang luar biasa menyayanginya. Meskipun kadang ketika berangkat bekerja putra kami menangisi kepergian saya. Saat itu hati saya mulai teriris. Ketika putra kami masuk rumah sakit karena sesuatu hal, saya menemaninya dua hari. Setelah itu kantor mengharuskan saya keluar kota. Masih saya ingat salah satu pembezuk yang masih kerabat kami mengatakan saya cukup ‘kuat’ meninggalkannya. Saat itu kondisi putra kami mulai membaik dan saya pikir dia berada ditangan yang tepat. Dokter. Dan kebetulan suami saya tidak sedang keluar kota. Apa yang salah?
Putra kedua kami lahir. Kami tidak menemukan pembantu sebaik seperti sebelumnya. Sampai dengan sekarang putra kedua kami belum lancar berkata-kata. Mungkin ketika kami bekerja tidak ada yang mengajaknya bercakap-cakap. Buktinya ketika saya cuti melahirkan anak ketiga selama tiga bulan. Kosa katanya meningkat. Di dalam relung hati yang terdalam saya menyalahkan diri saya sendiri. Jika saya selalu disampingnya, mungkin dia akan secerewet kakaknya.
Setiap kali akan berangkat ke kantor kami harus berputar-putar mengelilingi perumahan kami, bersama putra kedua kami. Jika tidak dia akan menangis histeris, sehingga kami miris. Seandainya saya bisa selalu membawanya. Mendekapnya selalu.
Ketika putri ketiga kami lahir. Proyek tempat saya terakhir bekerja usai April tahun ini. Usia putri kami enam bulan. Biasanya sebelum proyek yang satu selesai, saya sudah mendapatkan proyek lainnya. Namun tidak kali ini.
Saya merasa kehilangan waktu-waktu bersama mereka. Waktu-waktu yang tidak akan pernah kembali. Waktu mereka merangkak pertama kali, waktu mereka bicara pertama kali dan waktu waktu lain yang tidak akan pernah tergantikan. Saya takut saya akan menyesalinya kelak. Saya lebih takut lagi karena saya tidak tahu banyak kebiasaan mereka. Bagaimana kami akan berbincang, manakala saya tidak tahu topik-topik yang mereka sukai?
Seringkali saat saya berada diluar kota, saya mendapat kabar bahwa anak kami sakit. Duh, inginnya saya bisa terbang saat itu juga dan memastikan mereka tidak apa-apa. Atau saya berada di suatu tempat yang sangat indah, menyenangkan. Rasanya saya tidak bisa menikmatinya manakala saya hanya sendirian. Yang saya bayangkan adalah, alangkah bahagianya jika putra-putri kami juga bisa menikmatinya.
Saya punya teman-teman beragam. Ada yang sampai sekarang belum menikah dan menjadi wanita karir yang hebat. Ada yang sudah menikah, punya anak dan tetap menjadi wanita karir yang hebat. Ada juga teman saya yang sejak awal menikah memutuskan untuk berada dirumah saja. Sekarang saya jadi tahu, menjadi ibu adalah peran yang sungguh luar biasa. Sebagaimana salah satu iklan di televisi.
Ibu, disadari atau tidak adalah tenaga keuangan yang hebat, mencukupkan berapapun uang yang diberikan uantuk memenuhi kebutuhan rumah dan jika mungkin untuk ditabung. Ibu, adalah tenaga pengajar yang harus serba tahu karena menjadi rujukan setiap pertanyaan. Ibu, adalah perawat atau dokter yang ahli sehingga kasus pilek, panas karena sakit gigi bisa ditangani segera sebelum dibawa ke praktek dokter. Jika anaknya alergi, Ibu juga harus memastikan makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang tidak akan memicu alergi anaknya. Dan tugas-tugas lain yang dikerjakannya dengan penuh cinta.
Maka tidak salah jika pepatah mengatakan, dari ibu yang hebat akan muncul anak-anak yang hebat. Di dalam Islam dikatakan surga terletak dibawah kaki ibu.
Saya tahu itu, namun sungguh tidak mudah Kesibukan-kesibukan itu bukan kesibukan yang biasa saya jalani. Pekerjaan-pekerjaan ini bukan pekerjaan yang biasa saya lakukan. Namun memandang putra-putri kami, tangan mereka yang kadang memeluk leher saya dan minta cium setiap saat, adalah kekuatan tersendiri. Kata-kata ayah saya masih sering terngiang, namun saya tidak ingin mendebatnya. Saya hanya ingin berada disamping anak-anak kami. Memeluk dan mengelus mereka kapanpun saya mau. Mendengarkan cerita-cerita mereka setiap hari. Hanya itu.
Ketika keputusan itu, saya sampaikan pada salah satu teman, pertanyaannya adalah: Bisakah? Rasanya secara nalar memang tidak bisa, namun kenyataannya selama empat bulan ini dengan segala cerita didalamnya, saya bisa. Saya menikmatinya. Memastikan kepada putra-putri kami saya ada kapanpun mereka butuhkan. Mencintai mereka tanpa ada syarat. Tanpa ada habisnya. Meskipun, tidak mempunyai uang sendiri sungguh tidak nyaman.
Salah satu teman ada yang mengatakan, jika suatu saat kamu ingin bekerja lagi pasti akan sulit. Biasanya jika kita berhenti, jeda beberapa saat akan sulit mendapatkan pekerjaan lainnya. Entahlah, saya hanya ingin mengikuti naluri saya. Naluri saya sebagai seorang wanita, sebagai ibu. Mungkin memang ada yang mesti dikorbankan. Yang saya tahu, saya tidak akan menjadi wanita sempurna, hanya dengan melahirkan saja. Menurut saya, saya akan menjadi wanita yang sempurna jika anak-anak kami menjadi orang yang berguna bagi sesama, mampu berempati terhadap orang lain, mempunyai ahlak yang baik.
Saat inilah nilai-nilai itu mesti kami tanamkan bersama. Mungkin ada yang bisa, dengan tidak mendampingi mereka setiap saat. Dengan menekankan pada kualitas waktu. Masing-masing orang punya cara berbeda mengungkapkannya. Cara saya, mengikuti naluri saya, merengkuh mereka dalam pelukan. Membantu mereka menjadi diri sendiri. Mendampingi mereka meraih mimpi. Saat ini saya mesti menggandeng tangan-tangan mungil mereka, menunjukkan arah dan jalannya. Pekerjaan ini menurut saya, tidak bisa saya delegasikan kepada orang lain. Sehebat apapun mereka. Karena hanya saya ibu mereka.
Taman Indah, September 2, 2009.
Langganan:
Postingan (Atom)